
Tanah dan Masa Depan Masyarakat Adat Papua
Prolog
Manusia hidup di atas tanah. Manusia? Kata itu, menunjuk pada makluk
bernalar yang hidup dan melakukan aktivitas, berkembang, mengisi, dan
menguasai. Manusia ’terdampar’ di atas tanah dan secara otomatis
mempertahankan hidup dengan berbagai aktivitas di atasnya. Tanah menjadi
tempat melakukan aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2001:1132) tanah adalah
(1) permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; (2) keadaan
bumi suatu tempat; (3) permukaan bumi yang diberi batas; (4) permukaan
bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa…, dan seterusnya. Maka,
di atas tanah ada segala sesuatu termasuk manusia. Bagi manusia, tanah
menjadi tempat melakukan hubungan dengan segala sesuatu ’lain’ yang
ada—lingkungan– dan karenanya dapat hidup.
Dengan demikian, tanah (lingkungan) menjadi bagian hidup dan
keber’ada’an— dalam pandangan teologis, manusia diciptakan dari tanah,
manusia hidup di atas tanah, manusia akan kembali ke tanah, walaupun
tidak mudah dibuktikan (yang jelas, bila manusia mati, tubuhnya akan
dikubur atau dibakar dan kemudian terurai menjadi tanah dan gas alam
lainnya)– manusia. Berbicara soal tanah adalah juga berbicara soal
manusia dan lingkungan hidup. Maka, jika lebih jauh berbicara tentang
makna dan fungsi tanah, tidak perlu pula diartikan secara sempit.
Berbagai makna dan fungsi tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup
manusia dan makluk hidup lainnya.
Mathias Haryadi (tanpa tahun) mengemukakan, tiga arti fundamental
dari tanah. Pertama, tanah adalah tempat manusia mendirikan rumah. Di
atas tanah dan dalam rumah ia tinggal, manusia menemukan basis hidupnya.
Di sana, ia menemukan identitasnya. Kedua, di atas tanah itu, manusia
berhubungan dengan hewan dan tunbuh-tumbuhan (lingkungan—air, udara, dan
lainnya). Hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga, karena tanah
memiliki arti ekonomis yang sangat kaya, satu-satunya dan tak mungkin
tergantikan.
Keterpenuhan sandang, pangan, dan papan menjadi dasar untuk
mengartikan makna dan fungsi tanah. Sebagian besar masyarakat Indonesia
masih tergantung pada tanah (hutan). Menurut Abdon Nababan (2003), dalam
kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan (komunitas-komunitas
masyarakat adat) populasinya diperkirakan antara 50–70 juta orang masih
tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat
dengan lingkungan (tanah) lokalnya. Mereka tergantung pada alam serta
memiliki kedekatan, ikatan yang erat dengan alam termasuk tanah.
Masyarakat Papua merupakan bagian dari masyarakat adat dunia yang secara
turun-temurun hidup dan menghidupi dari dan di atas tanah mereka. Tanah
Papua menjadi hak milik yang diatur menurut hukum adat (KBBI,
2001:1132).
Tulisan ini hendak mengulas tentang cara pandang masyarakat adat
Papua tentang tanah (– serta isinya) dan ’pemanfaatan’ tanah dan isinya
oleh orang luar (pemerintah dan pengusaha). Pemanfaatan tanah (hutan dan
kaitannya) dengan perlindungan tanah (hutan)—pelestarian lingkungan
hidup– dengan mengakui hak-hak adat dengan sistem pemerintah yang baik
dan keterwakilan lembaga yang memikirkan secara serius akan hal ini,
ikut dipikirkan secara umum.
Tanah bagi Masyarakat Adat Papua
Masyarakat adat diakui secara internasional sebagai bagian dari
masyarakat dalam komposisi dan konstelasi sosial-politik masyarakat
modern (Baca: HAM Masyarakat Adat pasal 1, 2, dan 3– eksistensi dan jati
diri Madat). Mereka tidak masuk ke dalam kelompok Masyarakat Sipil,
Masyarakat Ekonomi ataupun Politik. Maka, jelas Madat berhak menikmati
segala hak yang seharusnya dimiliki dan dinikmati oleh semua umat
manusia di planet bumi ini, termasuk hak untuk menghargai dan mengatur
tanah (hutan—lingkungan hidup) yang merupakan sumber kehidupan dan
identitas (Papuapost.com, 19 Juni 2008).
Rakyat Papua sebagai bagian dari masyarakat adat Indonesia dan dunia,
sejak awal kehidupan, sudah sangat dekat dengan tanah (alam—lingkungan)
mereka. Mereka telah memiliki hak untuk menghargai dan mengatur tanah
(hutan) yang merupakan sumber kehidupan dan identitas mereka. Kedekatan
orang Papua dengan alam dapat dipahami melalui tarian, lagu, dan doa.
Salah satunya dapat dilihat dari ungkapan sederhan mama Yosepha
Alomang, peraih ”Goldman Enviromental Prize” (Selangkah, September 2006. Tanah Adat, Freeport, dan Warga Sipil” hlm. 26). Atas tanahnya yang direbut oleh negara dan kapitalis, dia mengatakan: ”Tanah ini saya punya tubuh. Gunung Nemangkawi ini jangtungku. Danau
wonangon ini saya punya sum-sum. Kali ini saya punya nafas. Tetapi Kao
sudah makan saya. Kao tidak punya hati dan perasaan. Freeport dan
Pemerintah, kamu sudah makan saya. Tidak sadarkah kamu?”
Ungkapan di atas memperlihatkan mitologi menyangkut manusia sejati
(seorang ibu) yang berubah menjadi tanah dan membentang sepanjang daerah
Amungsal (tanah Amugme)—daerah keramat wilayah PT Freefort beroperasi
sejak 1967 hingga saat ini. Tanah bagi Amugme adalah “seorang ibu” yang
baik hati, yang memberikan dan menyediakan semua kebutuhan.
Tidak hanya suku Amugme dan Kamoro. Sekitar 250-an suku yang ada di
tanah Papua dengan adat istiadatnya masing-masing memaknai tanah sebagai
ibu (mama). Orang Mee misalnya, selalu mengatakan, “maki kouko akoukai” (tanah
adalah Ibu—jagalah baik-baik). Orang Mungmen juga mamahami tanah
sebagai ibu kadung. Nimboran percaya bahwa tanah diciptakan oleh seorang
nenek tua, sedangkan bagi orang Humbuluk tanah dikonotasikan sebagai
rahim perempuan.
Masyarakat Napan di Nabire misalnya, meyakini bahwa hulu sungai Lagari yang dikenal dengan nama ‘Nuba Urigwa’
adalah tempat yang sakral, yang menjadi tempat tinggal Kuri. Keyakinan
ini membuat masyarakat dari kelompok budaya Kuri di kawasan
Napan-Weinami dan Makimi memahami seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS)
sebagai wilayah yang tidak boleh dirusak karena kehidupan sungai
bersumber pada tanah di sekitarnya. Tanah dianggap rahim bagi air sungai
dan air laut, sehingga laut dan sungai tidak boleh dicemari (baca: Kuri
dan Pasai). Sama juga masyarakat kampung Yaro di Kabupaten Nabire.
Mereka memandang tanah sebagai manusia yang harus dijaga.
Pada budaya Suku Ngalum, Kabupaten Pegunungan Bintang, setiap bidang
tanah, pohon, rotan, sungai, gunung hingga batu berhubungan erat dengan
suku-suku di sekitarnya. Begitu eratnya hubungan ini sehingga dalam
pembukan lahan, setiap laki-laki yang terlibat wajib memakan segumpal
tanah. Ini mencerminkan bahwa tanah merupakan sumber kesuburan dan
kehidupan sehingga masyarakat Ngalum harus mengikatkan dirinya dengan
tanah yang tidak lain dianggap sebagai ibu, (Tabloid Jubi, 20 Agustus 2007).
Keyakinan tanah sebagai ibu, diperkuat setelah agama kristen masuk di
tanah Papua. “Hormatilah ayah dan ibumu” (baca: Sepuluh Perintah
Allah). Ajaran itu semakin mendekatkan suku-suku di tanah Papua yang
mayoritas kristen itu bahwa tanah mereka sebagai ibu yang patut untuk
dicintai (dijaga).
Tanah bagi masyarakat adat Papua berperan dalam memperkuat ikatan
mereka dengan segala hal yang berada di permukaan bumi. Tanah dalam
stuktur dasar antropologi di kalangan orang Papua menyatu dengan
manusia. Artinya, tanah dipandang sebagai rumah yang memberi kehidupan
dan perlindungan. Tanah juga adalah tempat tinggal arwah nenek moyang
yang merupakan sumber kekuatan hidup manusia. Dari aspek budaya, tanah
adalah mama atau ibu. Ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara,
mendidik, membesarkan, hingga sekarang ini. Karena itu bila manusia
merusak alam, dengan sendirinya ia merusak dirinya sendiri. Dengan
demikian, masyarakat Papua memandang tanah sebagai “tubuh ibu atau mama”
orang Papua, sehingga tidak ada orang yang seenaknya mengambil atau
merusak.
’Perampasan’ Tanah Adat Papua
Tanah Papua merupakan ’mama’ masyarakat adat Papua yang dimiliki
secara turun-temurun. Tanah Papua dimiliki oleh suku-suku (baca: 250
suku di Papua). Dan, di lingkup suku dimiliki oleh marga-marga. Tanah
yang dimiliki oleh masyarakat adat itu mulai di’rampas’ sejak
kepentingan bisnis dan politik mulai menapakan tajinya di mana-mana,
terutama areal pertambangan, hutan, dan pembangunan jalan trans serta
lokasi pemukiman baru termasuk program transmigrasi.
Negara yang ‘baru’ lahir itu secara sengaja menjadikan eksistensi
masyarakat adat tidak memunyai kekuatan dan kepastian hukum, karena
dikalahkan oleh kepentingan yang mengatasnamakan negara demi kemakmuran
rakyat (Selangkah, Edisi Februari-April 2005). Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3, “Melaksanakan
hak ulayat masyarakat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
nasional, maupun peraturan-peraturann yang lebih tinggi.” Bunyi
UUPA 1960 Pasal 3 jelas-jelas menjadikan masyarakat adat tidak punya
jaminan hukum dari negara. Dengan berdasar pada pasal itu, negara
memperbolehkan dan memberikan HGU, HPH, mupun hak pertambangan kepada
perusahaan-perusahaan kayu maupun industri pertambangan. Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 juga dipakai negara sebagai alasan (surat
jalan) untuk menguasai tanah adat.
Secara yuridis kata ’menguasai’ yang terkandung pada pasal 33 ayat 3
UUD 45 memunyai makna; pertama, mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaannya. Kedua, menentukan dan
mengatur hak-hak yang dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa. Ketiga,
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Maka,
jelas bahwa negara tidak berhak memiliki. Kata mengatur,
menyelenggarakan, menentukan mengisyaratkan makna adminitratif, tetapi
seringkali makna tersebut diselewengkan oleh negara untuk kepentingan
penguasa dan pengusaha.
Undang-Undang Pokok Agraria dalam Bab II Pasal 16 diatur tentang hak
atas tanah, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yang meliputi: pertama,
hal milik; kedua, hak guna usaha; ketiga, hak guna bangunan; keempat,
hak pakai; kelima, hak sewah; keenam, hak membuka tanah, dan ketujuh hak
memungut hasil hutan. Pengaturan atas hak tanah di atas mengalami
penyimpangan, terutama oleh aparat pemerintah sendiri, (baca: R.H. De
Haas Engel dalam Pekey, 2007). Semua produk Undang-Undang tentang tanah
diterapkan sepihak tanpa rasa hormat terhadap hukum adat, dan prinsip
tentang tanah yang dianut oleh masyarakat adat. Aspek lingkungan yang
sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem yang
terkandung di dalamnya terabaikan.
Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang
mengawali masuknya PT Freeport Indonesia (PTFI) di tanah adat orang
Amugme dan Kamoro misalnya, kontrak dilakukan tanpa rasa hormat
terhadap hukum adat dan prinsip tentang tanah yang dianut oleh
masyarakat adat. Kontrak karya pertama ditandatangani pada bulan April
1961 dan mulai beroperasi pada 10 Januari 1967 tanpa pembicaraan dengan
pemilik tanah adat (Baca: ‘Travel Feature Itu Menuai Bencana’, Selangkah, edisi September 2006).
Penduduk Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro yang berada di
Mimika dipaksa merelakan tanah adat mereka yang memiliki nilai sosial
budaya, politik dan religius. Gunung Ertsberg atau Yelsegel Ongopsegel
di daerah Kabupaten Mimika yang merupakan daerah keramat orang Amungme
dan Kamoro harus rela isi perutnya dilubangi karena kepentingan emas,
perak dan tembaga demi sebuah investasi. Mereka menyaksikan tanah
keramat, tempat arwah leluhur bersemayam dibongkar tanpa merasa
bersalah dan tanpa ada perundingan. Mereka menyaksikan hak-hak adat
mereka terhadap tanah adat tercabik-cabik. Mereka menyaksikan
sungai-sungai tempat mereka mencari ikan dan berudu diracuni dengan
limbah.
Eksploitasi atas tanah adat (emas, kayu, tumbuhan, hewan, dan sebagainya) terus berjalan. Di wilayah adat Malamoi misalnya, setidaknya ada dua perkebunan kelapa sawit selain eksploitasi kayu. Kini hutan alam, yang secara turun-temurun menjadi sumber kehidupan, telah menjadi sumber petaka, yakni banjir dan longsor. Di Biak, hutan dibuka sejak masa Belanda hingga sekarang. Pembukaan hutan dengan masuknya investasi skala besar di Papua telah merusak struktur masyarakat adat dan cara pandang mereka terhadap tanah. Semua jenis kayu, (Merbau intria sp, matoa ketapang, bintangur dan damar) dibabat tanpa reboisasi. Kayu merbau merupakan komoditas yang penting dan "laris" di pasaran, maka habitat alam lain (sungai, kayu dan lainnya) diberangus rata dalam rangka mencari merbau, (baca: Papua 2008).
Data Forum Kerja Sama (Foker) LSM Papua tahun 2006 menunjukkan, ada
65 perusahaan HPH di Papua dengan luas konsesi 14,4 juta hektar (ha).
Dari 65 perusahaan HPH tersebut, hingga tahun 2006 hanya 15 HPH yang
masih aktif. Perusahaan HPH punya tanggung jawab, antara lain adalah
program ‘bina desa’. Artinya pemberdayaan masyarakat adat (kampung)
pemilik hak ulayat dalam bentuk pembangunan rumah warga, sekolah, gereja
atau fasilitas lainnya. Namun, hal ini selalu menjadi keluhan
masyarakat adat di berbagai areal HPH di tanah Papua.
Masyarakat adat Mee di distrik Yaro, kabupaten Nabire misalnya,
memilki pengalaman buruk dengan perusahaan HPH PT Sesco di wilayah adat
mereka. Perusahaan HPH PT Sesco yang beroperasi sejak tahun 1990/1991
hingga saat masih belum membayar sejumlah Rp40 juta dengan hitungan satu
kubik Rp1000,00. Ini artinya bahwa kubikasi yang merupakan kewajiban
mutlak saja belum membayar, apalagi melaksanakan program ‘bina desa’.
Perusahaan HPH yang masuk di daerah Yaro (daerah yang sama) pada tahun
2003, yakni PT Jati Dharma Indah justru mengklaim kayu termasuk segala
yang terkandung dalam tanah adalah miliknya. Bahkan dia melarang
masyarakat adat untuk mencari ikan, berburu kuskus, di tanah adat
mereka. Sementara PT Jati Dharma Indah menghabisi berbagai jenis burung
termasuk cenderawasih dengan senapan angin, termasuk kuskus dan kekayaan
hutan lainnya.
Pengalaman masyarakat adat Yaro yang digambarkan di atas adalah hanya
sekelumit dari kemungkinan kesamaan pengalaman masyarakat adat di 65
areal perusahaan HPH di tanah Papua. Data kemiskinan yang dipaparkan
sekretaris eksekutif Foker LSM Papua Septer Manufandu sungguh
memprihatinkan. Sebanyak 391.767 keluarga (81 persen) dari total 480.578
keluarga di Papua tergolong miskin. Data ini menunjukkan bagaimana
dampak eksploitasi sumber daya alam Papua bagi warganya. Juga, sekitar 4
juta ha lahan yang telah disiapkan bagi belasan perusahaan perkebunan
skala besar, 300.000 ha di antaranya kebun kelapa sawit adalah rencana
tragedi masyarakat adat Papua di masa depan. Eksploitasi atas tanah adat
Papua terus dilakukan di balik nomine ‘Heroes Environment 2007′ yang dianugerahi kepada Gubernur Suebu dari Majalah Time terbitan Amerika Serikat pada 25 Oktober 2007 di Royal Court of Justice London, Inggris.
Perampasan tanah adat oleh penguasa dan pengusaha ini merupakan
ancaman keutuhan hutan dan masyarakat adat. Pengampanye hutan Greenpeace
Asia Tenggara, Bustar Maitar, mengatakan, ancaman keutuhan hutan
(tanah) Papua bukan hanya dari pengambilan kayu, pertambangan dan kelapa
sawit (Kodeco dilaporkan menebangi hutan untuk perkebunan kelapa sawit
di wilayah Mamberamo), namun juga rencana pembukaan jalan raya dengan
pamrih kayu dan pemekaran daerah. (Kompas, 24 Juni 2008). Belum
puas dengan hutan dan tambang, berbagai spesies di atas tanah adat,
diramu dan dibawa keluar Papua. Berjuta-juta spesies burung, ikan air
tawar, reptil, amfibi, serangga air, kupu-kupu, mamalia kecil dan
vegetasinya telah hilang dan masih terus diburu.
Penghancuran lingkungan dan ekosistem termasuk perusakan hutan
lindung secara membabi buta ini mengancam eksistensi masyarakat adat
Papua. Masalahnya, Jabar Lahaji memprediksikan hutan Papua akan
lenyap antara tahun 2013 sampai 2015. Hasil analisa satelit tahun
1998-2000 menunjukkan angka deforestasi yang cukup tinggi, sekitar ,45
jua ha. Kalau hitungannya terus perpanjang sampai tahun ini, laju
deforestasi diperkirakan bisa mencapai 2,5 sampai 3 juta ha pertahun.
Kalau hutan di Kalimantan dan Sumatera diduga tahun 2005-2010 akan
habis, di Papua, antrian 2013-2015 (baca: Jabar Lahaji, 2008).
Nah, apa yang tersisa sekarang dan 2015 nanti? Yang tersisa adalah
persoalan demi persoalan yang terjadi, seperti rusaknya tatanan
kehidupan, menyangkut rusaknya (mite) mitologi yang terkait dengan
kerusakan lingkungan (obat-obatan dan kebutuhan lainnya), sosial,
politik dan sebagainya. Hal-hal itu melahirkan perlawanan masyarakat
adat Papua, lalu dihadapkan pada militer –yang dipiara di areal HPH dan
pertambangan– dengan stigma OPM (Organisasi Papua Merdeka). Stigma
oposan pemerintah dengan label OPM atau separatis sering digunakan
menjadi alat penekan terhadap masyarakat, bahkan sering terjadi kasus
penangkapan, pemukulan/penyiksaan dan penculikan.
Melangkah untuk Melingdungi Tanah Adat Papua
‘Perampasan’ tanah adat telah merusak manusia, tanah dan segala
isinya (hubungan manusia dengan alam) serta pranata-pranata
sosial-politik dan kultural masyarakat adat. Upaya-upaya
pemulihan-perlindungan adalah tantangan yang harus menjadi perioritas.
Dalam konteks ini, melangkah untuk melingdungi berpulang pada
penyesuaian dan penerapan hukum dengan kepastian hak-hak masyarakat
adat. Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Nomor 21 Tahun 2001,
Pasal 38 ayat 2 mengatakan, usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber
daya alam dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat,
memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha serta prinsip-prinsip
pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut,
pada Pasal 43 ayat 1 menegaskan, pemerintah wajib mengakui, menghormati
dan melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat
adat.
Undang-Undang Otsus Papua secara tegas memberikan pengakuan dan
perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak adat. Dalam hal ini,
pengakuan atas suatu kawasan SDA yang berada di dalam wilayah masyarakat
adat. Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak adat
tersebut, maka UU PSDA perlu menyebutkan: pertama, kawasan SDA yang
dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh masyarakat adat maka kegiatan
pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat itu sendiri.
Kedua, setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat
dengan pihak ketiga harus didasarkan pada kesepakatan yang saling
menguntungkan dengan memerhatikan aspek konservasi. Ketiga, setiap
kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak
luar negeri mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota dengan
memerhatikan kepentingan nasional tanpa merugikan masyarakat adat.
Perlu juga memikirkan, pemisahan hak penguasaan dengan hak guna, dan hak pengelolaan/pengusahaan. Peraturan
per-UU-an harus secara jelas membedakan antara “penguasaan kawasan dan
SDA yang ada di dalamnya” dengan “penggunaan kawasan dan SDA di
dalamnya”. Dengan demkian, status penguasaan/kepemilikan atas kawasan
SDA baik yang berstatus milik pribadi, milik kolektif dan hak
adat/ulayat, maupun milik publik bisa memiliki fungsi dan tata guna: (a)
produksi, yaitu kawasan tertentu yang SDA-nya bisa dikelola dan
diusahakan untuk memproduksi; (b) lindung, yaitu kawasan tertentu yang
harus dilindungi fungsi ekologis/hidrologis di mana pemanfaatan SDA di
dalamnya harus dilakukan secara sangat terbatas; (c) konservasi, yaitu
kawasan yang sumberdaya dan keanekaragaman hayati di dalamnya harus
dilestarikan.
Pengakuan penguasaan kawasan adat jelas akan memiliki implikasi pada
mekanisme dan prosedur penentuan masyarakat lokal untuk diakui sebagai
masyarakat adat, dan juga untuk menentukan batas-batas wilayah dan
kawasan hutan adat dari masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, harus
jelas mengatur kriteria-kriterianya, yang kemudian secara
operational-prosedural diatur lebih terinci dalam suatu aturan—dalam hal
ini peraturan daerah khusus (Perdasi) yang mengatur tentang “Hutan
Adat”. Yang perlu diwaspadai adalah agar proses penentuan masyarakat
adat dan batas-batas wilayah/kawasan adat tidak berada di tangan
pemerintah atau pihak lain, tetap ditentukan sendiri oleh masyarakat
adat yang bersangkutan secara partisipatif dan prosesnya harus dimulai
dari tingkat kampung atau satuan sosial terendah—antara lain untuk
melindungi konflik tingkat masyarakat adat.
Sementara itu, untuk menjamin keberlanjutan fungsi layanan
sosial-ekologi alam dan keberlanjutan sumber daya alam dalam cakupan
wilayah yang lebih luas maka pendekatan perencanaan SDA dengan instrumen
penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan
kesatuan layanan ekosistem, endemisme dan keterancaman kepunahan
flora-fauna, aliran-aliran energi sosial dan kultural, kesamaan sejarah
dan konstelasi geo-politik wilayah.
Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka pilihan-pilihan atas sistem
budidaya, teknologi pemungutan/ekstraksi SDA dan pengolahan hasil harus
benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan ekologi. Dengan pendekatan
ekosistem yang diperkaya dengan perspektif kultural seperti ini tidak
ada lagi “keharusan” untuk menerapkan satu sistem PSDA untuk wilayah
yang luas. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap ekosistem bisa jadi akan
membutuhkan sistem pengelolaan SDA yang berbeda dari ekosistem di
wilayah lain.
Keberhasilan kombinasi beberapa pendekatan seperti ini membutuhkan
partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat adat dalam proses
penataan ruang dan penentuan kebijakan pengelolaan SDA di wilayah
ekosistem. Semakin tinggi partisipasi politik dari pihak-pihak
berkepentingan akan menghasilkan rencana tata ruang yang lebih
akomodatif terhadap kepentingan bersama untuk banyak komunitas yang
tersebar di seluruh wilayah ekosistem tersebut. Dalam konteks ini maka
membangun kapasitas masyarakat adat yang berdaulat (mandiri) harus
diimbangi dengan jaringan kesaling-tergantungan antarkomunitas dan
antarpihak. Untuk bisa mengelola dinamika politik di antarpihak yang
berbeda kepentingan seperti ini dibutuhkan tatanan organisasi birokrasi
dan politik yang partisipatif demokratis.
Epilog
Akhirnya, mengingat tanah bagi masyarakat adat Papua berperan dalam
memperkuat ikatan mereka dengan segala hal yang berada di permukaan
bumi, maka kemungkinan penerapan hukum adat dalam pengaturan kehidupan
masyarakat adat, pengakuan kedaulatan masyarakat adat, dan kepatuhan
penguasa dan pengusaha terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia—(banyak yang telah mati, dikubur dan kemudian terurai menjadi
tanah dan gas alam lainnya di atas tanah adat mereka)–perlu direnungkan.
Pemerintah dan pemerintah provinsi Papua perlu mengevaluasi kembali
semua undang-undang dan peraturan terkait, termasuk meninjau program
transmigrasi—telah berbuah pahit– dan arus migrasi dari luar Papua yang
mengancam eksistensi tanah dan masyarakat adat Papua (baca: 6 tahun
Otsus Papua). Hak-hak adat tidak dipikirkan dengan baik, dapat
bermuara pada gugatan masyarakat adat Indonesia—Papua, Kalimantan
(Borneo), Sulawesi Utara, Riau, Maluku dan lainnya– terhadap sifat kesatuan negara Indonesia, karena masyarakat adat ada jauh sebelum negara ada. [Yermias Degei/MS]

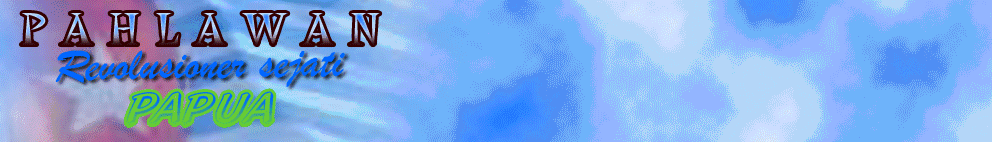


.jpg)
