
MIFEE Datang, Merauke Tenggelam
Suatu Fenomena Perampasan Tanah Milik Masyarakat Adat Papua
Oleh : Ley Hay*)
Tanah beserta segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan,
binatang, dan bahan tambang/mineral sebagai karunia Allah Sang Pencipta
Semesta Alam yang harus dikelola secara bijaksana agar dapat
dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasil guna serta berkelanjutan bagi
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik untuk generasi sekarang
maupun yang akan datang. Patutlah kita bersyukur bahwa Negara Indonesia
mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa dan kekayaan alam itu
hampir tersebar merata di seluruh kepulauan nusantara. Setiap pulau di
dalam wilayah NKRI memiliki keunikan tersendiri, seperti halnya
keanekaragaman hayati yang terdapat di Tanah Papua. Namun, tidaklah
berarti bahwa pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara berhak
menguasai segala kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah, hutan,
laut dan sungai bahkan udara di nusantara ini. Sebab, sejak sebelum
adanya Indonesia sebagai sebuah negara, wilayah darat maupun laut di
sebuah pulau seperti Tanah Papua sudah ada pemiliknya, yakni orang asli
setempat yang disebut sebagai masyarakat adat Papua.
Dalam beberapa literatur, Papua sering dikenal orang sebagai negeri
bunga anggrek dan burung Cenderawasih. Bagi para sejarahwan dan ahli
geografi, Papua dipandang sebagai kelangsungan Benua Australia yang
letaknya di zona tropika dengan berdasarkan pada topografi, alam
tumbuh-tumbuhan dan hewannya. Diperkirakan, pada masa purba Papua
menjadi satu daratan dengan benua Australia, pada tempat yang sekarang
merupakan Selat Torres yang lebarnya kurang lebih 100 Km. Karena dihuni
oleh bangsa negroid, maka pulau ini digolongkan pada gugusan Melanesia
sebagai induk bangsa yang berkulit hitam atau melanoderm. Dua peneliti
Papua terkenal yang berkebangsaan Prancis, yakni Villeminot suami-istri
mendefinisikan Papua melalui karyanya yang berjudul : La Nouvelle
Guinee, 700.000 Papous Survivant de la Prehistoire (Irian, 700.000 Papua
yang Keluar dari Zaman Prasejarah). Walaupun didukung oleh ensiklopedi
Grand Larouse Encylopedie, namun Ensiklopedia Indonesia yang didukung
oleh Encyclopedia Britannica menyatakan bahwa hanya daerah pesisir Timur
Irian yang termasuk Melanesia.
Istilah papua yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada
pengertian Tanah Papua yang secara administrative terdiri atas Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat. Sebagian besar penduduk Papua, terutama
di kawasan pedesaan, adalah masyarakat adat yang berdiam di dalam dan di
sekitar hutan. Kebudayaan masyarakat adat di Papua maupun Papua Barat
masih kental diwarnai oleh tradisi lisan atau budaya tutur dan ritual
adat istiadat. Papua dan Papua Barat bersama dengan Nangroeh Aceh
Darussalam adalah propinsi-propinsi di Indonesia yang memiliki
kekhususan dalam sistem politik pemerintahan Indonesia dengan status
otonomi khusus.
Propinsi Papua dan Papua Barat merupakan kawasan dengan tutupan hutan
yang paling luas di Indonesia dengan tingkat keanekaragaman hayati dan
keunikan yang tinggi, memiliki potensi fungsi ekologi, sosial dan
ekonomi yang tinggi serta berarti penting bagi iklim global. Hutan
Indonesia merupakan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Amazon
di Brazil dan Congo Basin di Kongo, dimana hutan yang sebagian besar
masih utuh saat ini adalah hutan Papua sebab kondisi terkini dari hutan
di Kalimantan, Sumatra, Jawa dan Maluku sebagaian besar telah habis.
Dari total luas tutupan hutan Indonesia, 2009: 88,17 juta hektare,
persentase total tutupan hutan di Papua adalah 38,72% (tertinggi dari
semua daerah di Indonesia).
Fenomena Perampasan Tanah Global
Berita tentang fenomena perampasan tanah (land-grab) muncul dari
seluruh dunia. Perampasan tanah dapat digambarkan sebagai suatu proses
di mana kepemilikan tanah yang dianggap “kosong”, “tidur” atau “tidak
produktif” berpindah tangan dengan transaksi yang menggiurkan, untuk
dikembangkan menjadi perkebunan skala besar untuk menghasilkan pangan
atau agrofuel, atau keduanya. Jumlah kesepakatan dan luas kawasan yang
tercakup meningkat pesat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam
beberapa tahun terakhir ini antara 20-80 juta hektare tanah. telah
“dirampas”, meskipun sulit dipastikan karena sebagian besar kesepakatan
itu dibuat dengan diam-diam.
Pendukung perampasan tanah mengatakan bahwa yang mereka lakukan
adalah investasi yang sangat diperlukan di sektor pertanian. Meskipun
jelas bahwa investasi diperlukan di daerah pedesaan dan pertanian,
pertanyaannya adalah apakah transaksi tanah skala besar seperti ini akan
menghasilkan jenis pembangunan yang kemungkinan besar akan bermanfaat
bagi masyarakat setempat. Jika diamati lebih dekat, jelas bahwa yang
terjadi bukannya pembangunan pertanian, tetapi pembangunan ‘agribisnis’
terus meningkat. Perbedaan keduanya jelas dan seharusnya tak ada lagi
kebingungan mengenai siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang
akan dirugikan oleh transaksi-transaksi itu.
Pelaku di balik akuisisi tersebut adalah perusahaan transnasional
besar atau pemerintah yang memanfaatkan sumber daya tanah “tidur” untuk
mengamankan ketahanan pangan dan energi dalam negeri. Kenyataannya,
tanah itu tidaklah “kosong”, melainkan seringkali merupakan tempat
tinggal warga setempat atau masyarakat adat yang telah hidup di sana
turun-menurun, tetapi hak mereka atas tanah itu tidak diakui atau
dihormati.
Terdapat sejumlah faktor yang mendorong perampasan tanah ini.
Faktor-faktor ini dapat dianalisis dalam konteks keuangan, pangan,
energi dan krisis iklim global. Krisis pangan global 2007-2008, yang
mendorong kenaikan harga pangan, menciptakan momentum politik dan
ekonomi bagi akuisisi tanah. Demikian juga, perubahan iklim dan krisis
energi menciptakan kebutuhan mendesak baru untuk mencari tanah bagi
produksi tanaman energi terbarukan.
Semua krisis global ini menumbuhkan persepsi bahwa—karena jumlah
penduduk diperkirakan meningkat sementara sumber daya terbatas—
permintaan akan pangan dan bioenergi akan terus meningkat. Pada
gilirannya, volatilitas harga komoditas menimbulkan kekhawatiran akan
ketahanan pangan dan energi. Meskipun kekhawatiran akan ketahanan pangan
mungkin tidak sebesar kekhawatiran ketahanan energi, tetapi keduanya
menimbulkan kebutuhan atas tanah.
Ada sejumlah pelaku utama yang tindakannya mendorong kenaikan pangan
dan akuisisi tanah. Secara umum mereka berasal dari sektor bisnis,
keuangan dan pemerintahan. Krisis keuangan global dan krisis pangan
global tahun 2007-2008 yang saling terkait turut menumbuhkan persepsi
bahwa tanah dan pangan perlu diamankan dan didapatkan. Kedua krisis itu
meningkatkan akuisisi tanah secara dramatis.
Fenomena Perampasan Tanah di Papua
Sejak jaman Orde Baru di bawah pemerintahan rejim Soeharto sampai
sekarang ini, Papua (sebelumnya Propinsi Irian Jaya) selalu menjadi
target utama proyek-proyek pembangunan skala besar dalam pengelolaan
sumberdaya alam. Pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI),
perkebunan Sawit, dan pertambangan adalah sejumlah projek pembangunan
skala besar yang telah puluhan tahun dikembangkan di seluruh Tanah Papua
(mencakup Propinsi Papua dan Papua Barat).
Semua proyek-proyek pembangunan skala besar tersebut terjadi di atas
tanah adat milik masyarakat asli papua, disebabkan oleh pemerintah yang
berkongsi dengan investor dan didukung oleh kekuatan militer merampas
berjuta-juta hektar tanah. Watak ekploitatif yang tertanam dalam otak
pemerintahan Rezim Orde Baru menyebabkan hutan dan kekayaan alam papua
hampir habis. Papua dijadikan lahan dan pemasok bahan baku untuk
industry di Negara maju. Sangat disayangkan, bahwa praktek-praktek
seperti itu masih diterapkan hingga kini, seperti hadirnya mega proyek
MIFFE di Merauke.
Tren perampasan tanah di papua dan seluruh nusantara menunjukkan
bahwa, pemerintah Indonesia lebih condong mengikuti kemauan dan
kepentingan kapitalisme global. Pemerintah Indonesia tidak lagi menjadi
pelindung dan pengayom masyarakat. Pemerintah tidak lagi mengutamakan
kepentingan Negara dan bangsa. Pemerintah secara sadar telah menjadikan
dirinya agen “kaki-tangan” kaum pemodal. Kasus Bima dan Mesuji dan
beberapa konflik agraria di Indonesia, seharusnya menyadarkan rakyat
bahwa, Negara Indonesia secara politik memang telah merdeka dan diakui
oleh dunia internasional, namun secara ekonomi belum mandiri karena
masih terjajah. Buktinya, rakyat banyak yang miskin, pendidikan tidak
merata, gizi kurang, perampasan tanah, pembunuhan, pengusiran komunitas
masyarakat adat, merajalelanya korupsi, lemahnya penegakkan hokum, dan
sejuta masalah lainnya.
(Integrated Food and Energy Estate, MIFEE)
Salah satu perampasan tanah yang paling kontroversial di Indonesia
saat ini adalah Proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke
(Integrated Food and Energy Estate, MIFEE), yang tengah dikembangkan di
bagian selatan Papua, di Kabupaten Merauke. MIFEE adalah mega proyek
yang meliputi 1,28 juta hektare perkebunan komersial yang diklaim
sebagai bagian dari visi Presiden Yudhoyono yang meragukan, yaitu
“pangan untuk Indonesia, pangan untuk dunia”.
Sejauh ini paling sedikit 36 investor sudah mendapatkan ijin konsesi.
Sebagian besar investor berasal dari Indonesia, tetapi perusahaan
Jepang, Korea, Singapura dan Timur Tengah kelihatannya juga terlibat.
Komoditas utama yang akan diproduksi oleh MIFEE adalah kayu, sawit,
jagung, kedelai dan tebu. Hingga pertengahan 2011, lebih dari setengah
lusin investor yang mendapatkan ijin untuk MIFEE tampaknya sudah mulai
bekerja di area konsesi mereka, termasuk perusahaan yang terkait dengan
Medco dan kelompok Rajawali yang berpengaruh. Meskipun MIFEE masih dalam
tahap awal, terdapat kekhawatiran serius akan implikasi sosial dan
lingkungan dari proyek ini terhadap penduduk setempat dan penghidupan
mereka.
MIFEE digembar-gemborkan sebagai kesempatan pembangunan, yang akan
menciptakan lapangan pekerjaan tidak hanya untuk warga Papua setempat,
tapi juga pekerja transmigran. Proyek itu juga disebut-sebut akan
mendorong ketahanan pangan nasional, serta ketahanan energi. Tetapi pada
kenyataannya sebagian besar konsesi tanah dialokasikan untuk perkebunan
kayu industri (lebih dari 970.000 ha), sementara sawit (lebih dari
300.000 ha) dan tanaman pangan (69.000 ha) berada pada urutan kedua dan
ketiga. Data ini menunjukkan bahwa motivasi utama MIFEE bukanlah demi
ketahanan pangan dan energi, tetapi kepentingan ekonomi.
Laporan dari desa-desa yang terimbas selama ini menunjukkan bawa
MIFEE merupakan ancaman serius bagi masyarakat setempat. Masyarakat adat
yang terlibat dalam kesepakatan dengan perusahaan telah ditipu dengan
pembayaran kompensasi yang sangat rendah sebagai ganti rugi ‘penyerahan’
tanah warisan turun-menurun dan menjadi bagian dari warisan budaya
mereka. Proses akuisisi tanah bersifat tidak transparan, dengan
intimidasi dan ancaman akan keamanan terutama karena kehadiran militer
di sana. Informasi mengenai potensi dampak proyek atas hidup mereka dan
hak apa saja yang mereka miliki untuk menolak atau menerima tawaran
perusahaan hanya sedikit yang sampai ke warga desa. Organisasi
masyarakat sipil setempat juga melaporkan bahwa pertemuan untuk
meningkatkan kapasitas diwarnai dengan interupsi oleh militer, yang
menggunakan keamanan nasional sebagai alasan untuk mengancam warga dan
menghentikan pertemuan. Jadi, dalam banyak hal, MIFEE adalah perampasan
tanah dengan motivasi politik dan ekonomi dengan lebih banyak ancaman
daripada kesempatan bagi masyarakat yang terimbas.
Pertanyaan penting, mengapa tanah papua dijadikan lahan dan target
eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran? Apakah semua proyek
tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat adat papua atau justru
sebaliknya? Sudah sejahterakah masyarakat papua atau belum? Mengapa
praktik kotor yang sarat dengan motivasi ekonomi politik semakin subur
terjadi di tanah papua? Bagaimana pola pemanfaatan sumberdaya alam yang
baik dan benar dengan memperhatikan aspek kelanjutan dan kelestarian
alam?
Jawaban singkatnya, kehadiran berbagai proyek-proyek pembangunan
raksasa di tanah papua selama ini tidak membawa dampak pada
kesejahteraan masyarakat adat Papua sebagai kelompok masyarakat yang
mewarisi tanah tersebut dari para leluhurnya. Yang terjadi adalah,
masyarakat di tipu, di bujuk, di bunuh, di kejar, di rampas tanahnya, di
langgar haknya sebagai sesame manusia. Bukan kesejahtetraan yang
dinikmati, justru kemisiskinan, gisi yang buruk, pelayanan kesehatan
yang minim, dan harapan akan adanya keadilan bagaikan mimpi yang tak
pernah nyata.
Salah satu sebab utama dari kenyataan ini adalah hak-hak masyarakat
adat Papua terhadap tanah dan sumberdaya alam selalu diabaikan dalam
pelaksanaan berbagai proyek tersebut. Akibatnya, di samping merebaknya
kemiskinan, timbul berbagai konflik antara masyarakat adat dan pihak
perusahaan dan negara (pemerintah). Konflik-konflik tersebut muncul
dalam berbagai bentuk dan tingkat keseriusan: mulai dari sekedar
demonstrasi, protes ke lembaga pemerintah, sampai konflik yang disertai
kekerasan.
Situasi konflik menimbulkan dampak makin berat bagi masyarakat adat
Papua di tengah kenyataan tidak diakuinya hak mereka. Bahkan dengan
statusnya yang khusus melalui UU Otsus Papua, masyarakat adat Papua
tidak kunjung melihat terang harapan akan adanya pengakuan hak mereka
sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan budaya
mereka.
Akhirnya secara sadar, marilah kita secara bersama melihat sejumlah
masalah yang terjadi di seluruh nusantara terkait dengan perampasan
tanah milik rakyat. Kita harus yakin, bahwa kekuatan rakyat tak dapat
dikalahkan. Sudah saatnya, rakyat harus di didik, di latih dan dibekali
dengan sejumlah informasi, pengetahuan, dan skill agar mereka mampu
bekerja dan menghidupi dirinya, agar mereka mandiri dan mampu berdiri
tegak menjaga, melindung dan memberdayakan hak miliknya kelangsungan
hidup mereka kini dan anak cucunya kelak.
Aiansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Jogjakarta
*) Mahasiswi Atma Jaya Jogjakarta, Jurusan Teknik Sipil

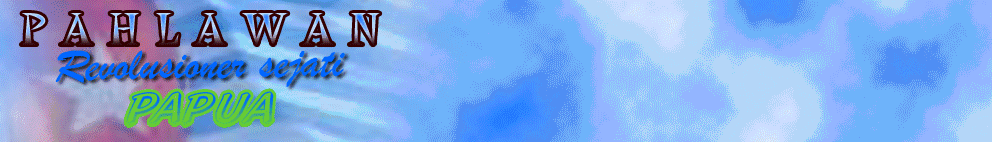


.jpg)
