
Memoria Pasionis di Papua: Sebuah Perspektif Filsafat ke-Tuhan-an
Oleh Ernest Pugiye*)
Sejak Papua dianeksasi dalam Indonesia melalui Trikora, rakyat Papua
tidak pernah hidup dalam suasana damai. Trikora menjadi awal penderitaan
orang Papua. Rakya Papua dari ke hari hidup dalam dunia kegelapan,
penderitaan dan kemelaratan. Ingatan akan penderitaan (memoria pasionis)
ini memacu rakyat Papua untuk melahirkan perlawanan. Ada banyak aksi
yang dilakukan orang Papua untuk menarik perhatian Indonesia dan
Internasional.
Ada dua pertanyaan mendasar. Mengapa rakyat Papua masih hidup tidak
damai dan rasa asing dari negara Indonesia? Bagaimana membangun budaya
damai di Papua?
Paradigma Negatif
Pemerintah Indonesia memandang rakyat Papua sebagai separatis, makar
dan manusia tidak beradap serta manusia kelas nol. Pemerintah Indonesia
dalam membangun rakyat tidak melihat sebagai warga komunitas Indonesia.
Padahal rakyat Papua telah dipersatukan oleh Indonesia sendiri melalui
Pepera 1961. “Pancasila” pada sila ketiga telah menegaskan juga
“Persatuan Indonesia”. Rakyat Papua telah mengakui diri sebagai warga
Indonesia dan kini sudah berumur 50 tahun.
Keberadaan Rakyat Papua bersama NKRI selama 50 tahun merupakan hal
amat penting dan lama. Selama 50 tahun itu, rakyat Papua menilai
kemanusiaan dan manusia Papua ini tidak dihargai oleh Indonesia. Lebih
banyak adalah paradigma negatif. Negara justru melahirkan berbagai
kebijakan yang menindas. Program penindasan yang paling baru adalah UP4B
(Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat).
Harus diakui, Indonesia gagal meng-Indonesia-kan orang Papua.
Akibatnya nilai kesatuaan sebagai warga Indonesia telah merosot. Rasa
tidak senang, ketidakpercayaan dan saling mencugai di antara rakyat
Papua dan Indonesia menjadi sebuah budaya sekular yang tak mudah untuk
dituntaskan.
Pembungkaman Nilai Kemanusian
Hampir semua orang Papua tahu bahwa nilai kemanusiaan mereka
dibumkam. Sepanjang sejarahnya, rakyat Papua tidak pernah dihargai
sebagai manusia sejati, seperti sesama lain. Keluhuran dirinya sebagai
manusia yang secitra dengan Allah tidak pernah dihormati dan
diperhitungkan dalam berbagai aspek kehidupan.
Hal itu terbukti dengan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi sejak
Pepera 1 November 1961, Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha
(1967-1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan
II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), dan Operasi Sapu Bersih III
(1985) sampai kini masih diperaktekkan oleh TNI dan Polri atas nama
negara (baca: Memoria Pasionis).
Hingga saat ini, berbagai tindakan kejahatan kemanusia yang paling
berat, kompleks dan memakan proses yang amat panjang untuk dituntaskan
secara komprehensif dan menyeluruh. Ketika terjadi masalah kemanusiaan,
maka lahir pula masalah kemanusiaan baru yang lain. Dan peristiwa tragis
semacam ini menjadi kegiatan rutin di kalangan rakyat Papua. Masalahnya
menjadi berbelit-belit di antara rakyat Papua dan Indonesia. Nilai
kemanusiaan itu menjadi terpenjara dalam berbagai kompleksitas masalah
baik masalah yang terjadi secara sadar atau tidak sadar, baik yang
horizontal maupun vertical di Papua.
Berbagai pelanggaran HAM secara fisik dan psikis di Papua belum
banyak terpublikasi. Pers lokal dan nasional seakan tutup mata. Negara
melarang pers luar asing masuk ke Papua. persoalan semakin rumit dan
tertutup.
Pemekaran Wilayah dan Manusia
Otonomi Khusus tidak bicara soal pemekaran. Namun, selama 10 tahun
Otsus, tanah Papua dibagi menjadi dua provinsi dan menjadi 38 kabupaten.
Pemekaran merupakan lahan konflik dan kebunnya para migrasi. Daerah
dimekar, manusia dikotak-kotak. Semua aspk dikuasai kaum pendatang tanpa
proteksi secara resmi dari pemerintah.
Seluruh eksistensi orang Papua sebagai satu ras (Melanesia)
terluluhlantakan. Tubuh dan jiwa tercabit-cabit ulah pemekaran.
Keretakan keluarga tumbuh subur. Kondisi ini semakin membuat orang tidak
memiliki kesadaran sebagai warga Indonesia. Nilai-nilai Pancasilais
yang merupakan indentitas negara tidak dihayati di Papua. Rakyat Papua
mengalami kehilangan harapan dan kepercayaan. Karena, jiwa telah
dimekarkan dari tubuh. Semua orang tampak tidak memunyai rasa
prikemanusiaan terhadap diri dan sesamanya sebagai warga komunitas
Indonesia. Pandangan Genosida bukan saja pembunuhan fisik menjadi jelas
dan nyata.
Filisofi “Harga Mati”
Filosofi yang dibangun oleh Indonesia dan pejuang Pembebasan Papua
Barat adalah “NKRI Harga Mati” dan “Papua Harga Mati”. Setiap pihak
bersikukuh dan mengklaim pihaknya di posisi paling benar. Ungkapan yang
menggerogoti keluhuran martabat manusia: “Koo….Epenkah?” menjadi sebuah
jiwa di antara setiap mereka dalam pengalaman hidup praksis.
Mereka dua adalah manusia penting, “Epen”. Yang tidak penting adalah
konsepnya yang keliru yakni konsep “Harga Mati”. Konsepnya dinilai
keliru dan tidak penting karena ada potensi yang mengamcam kehidupan.
Ancaman kehidupan di antara kedua pihak yang bertikai selama ini yakni
rakyat Papua dan pemerintah Indonesia justru terjadi karena didorong
oleh filosofi ‘Harga Mati”.
Dalam konteks hidup semacam ini perlu dicarikan alternatif, jalan
tengah. Lebih jauh, kedua pihak mesti bebas dari dirinya sendiri,
filosofi “Harga Mati” dan ketertutupan hatinya. Mereka mesti
menstransensikan diri dari dunia imitasi yang paling massif dan tidak
hidup ini.
Merajut Kebebasan dan Berdialog Damai
Merajut kebebasan dan dialog damai merupakan sebentuk upaya pemulihan
Papua sebagai tanah damai. Hal ini sangat penting bahkan menjadi sebuah
unsur yang paling ensensial karena tanpa pembebasan dan berdialog damai
mereka akan dibuai dan dimakan oleh kedangkalan konsep, filosofi dan
kegelapan hidupnya masing-masing.
Upaya kebebasan dan dialog damai menjadi sarana atau mendia untuk
menganalisa, mengindetifikasi dan mencari solusi atas semua konsep yang
keliru dan berbagai konflik kemanusia lain yang terjadi secara konkret
di Papua. Saya percaya, mereka dapat memepertanggungjawabkan semua
realitas penderitaan manusia Papua berdasarkan argumentasi-argumentasi
yang mengutamakan kebaikan bersama (bonum comune) sambil mencari solusi yang memuaskan antara kedua bela pihak yang bertikai (rakyat Papua dan pemerintah Indonesia).
Nilai fundamental dan universal seperti keadilan, kedamaian,
kebebasan dan cinta kasih dan mengangkat martabat manusia menjadi
inspirasi utama dalam mengembangkan karya kebebasan dan dialog damai
dengan melibatkan pemerintah luar negeri sebagai pihak netral. Rakyat
Papua dan pemerintah Indonesia mesti menolak pihak-pihak yang mau
menuntaskan masalah Papua dengan kekerasan. Langkah ini adalah jalan
menuju Papua tanah damai yang sesungguhnya.
*) Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura, Jayapura Papua

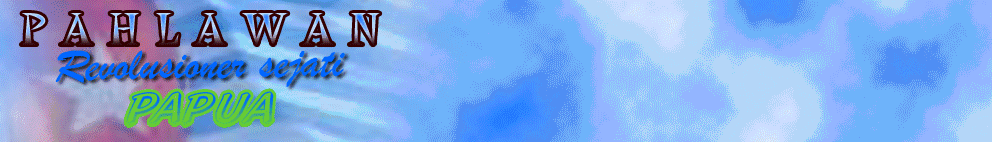


.jpg)
